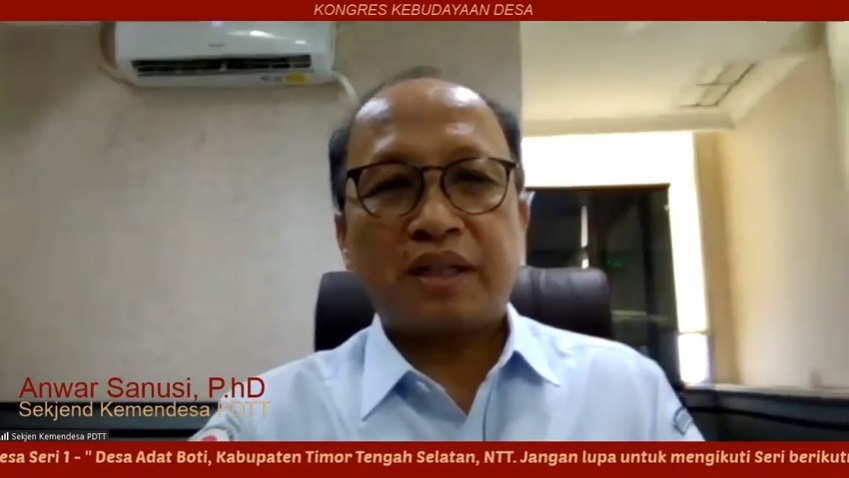Sekilas mungkin orang mungkin menyangka bahwa tidak ada potensi pertanian yang bisa dimanfaatkan dari bentang alam di Bolatena, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Alamnya sungguh menantang bahkan ada julukan bukan lagi tanah yang dipenuhi bebatuan, melainkan batu yang bertanah.
Namun siapa sangka, dari kondisi tersebut alam ternyata menunjukan keajaibannya. Ya, di balik tanah berbatu itu, tumbuh berbagai macam tumbuhan pangan semisal sorgum yang menjadi andalan, beras merah, jagung pulut, beras hitam serta jawawut. Berbagai potensi ini terus menunggu tangan-tangan bijak yang mampu mengolah dan mengelolanya sehingga bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan warga.
Beruntung, warga di NTT memiliki semangat yang sama. Anak-anak muda, tokoh masyarakat, kaum perempuan hingga anak-anak pun dilibatkan dalam membangun desanya. Semisal dalam pembangunan jalan, penanaman sorgum, pembangunan aliran sungai untuk pengairan hingga program penanaman mangrove.
“Batu bertanah inilah yang memicu ide dan kesadaran warga, menyulap keterbatasan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan,” tandas Maria Loretha, Penggagas Pertanian Sorgum, Adonara Flores Timur yang menjadi salah satu narasumber Webinar Seri ke-7, Kongres Kebudayaan Desa pada Sabtu (4/7/2020).
Tak hanya berhenti pada sektor pertanian, kecantikan bunga sorgum bahkan dijadikan agrowisata dan ekowisata.
“Dengan sorgum, desa bisa berdaya. Sorgum bergizi, sorgum berduit,” tambahnya.
Dalam webinar bertajuk Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru tersebut, Maria mengingatkan bahwa ada ancaman yang nyata terhadap potensi-potensi lokal sebagaimana yang dimiliki Flores Timur.
Tanaman pangan yang menjadi ciri khas daerah itu, terancam karena pemerintah mendatangkan benih dari pulau jawa utamanya untuk tanaman padi.
Maria melihat bahwa ini ada kaitannya dengan pandangan bahwa sorgum masih dianggap sebagai tanaman inferior, sementara pemerintah masih mengutamakan Pajale atau Padi, Jagung dan Kedelai. Imbasnya adalah penyeragaman tanaman pangan termasuk di antaranya memaksakan untuk diaplikasikan di daerah-daerah yang mempunyai tanaman pangan yang khas.
“Penyeragaman bahan pangan yaitu berupa padi menimbulkan persoalan ketahanan pangan di desa,” tambah Maria.
Ini menjadi persoalan pelik utamanya terkait dengan ketahanan pangan di tingkat lokal. Bahkan Maria menyebut, jika hal itu terus dipaksakan maka selamanya mereka tidak akan maju.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan perlunya pelibatan semua pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terutama dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dan yang terpenting semua pihak di tingkat lokal harus pula dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan program pembangunan.
Pandangan serupa disampaikan Nissa Wargadipura, narasumber webinar dari Pesantren Ekologis At-Thariq Garut. Ia melihat jelas bahaya di balik pola pertanian yang monokultur.
“Warga desa dan kota menjerit karena kekurangan pangan selama pandemi covid-19, karena pola pertanian monokultur,” tandasnya.
Oleh karena itu, penting artinya untuk membuat keragaman bahan pangan sehingga masyarakat tidak tergantung pada satu komoditas tertentu.
Ahmad Nashih Luthfi dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional pun memberikan warning serupa.
Jangan sampai Indonesia tergantung pada satu komoditas yang sama. Solusinya adalah dilakukannya upaya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan, utamanya ketergantungan pada padi.
“Kita perlu belajar tidak bergantung hanya pada komoditas yang sangat manja. Padi kan sangat manja, harus ada airnya, pupuknya, penyiangannya juga diperhatikan,” tambahnya.
Namun persoalannya tak berhenti di situ. Desa juga menghadapi masalah ketersediaan lahan yang kian memperihatinkan. Alih fungsi lahan terjadi di mana-mana, cilakanya lahan-lahan yang ada di desa pun hanya dikuasai oleh segelintir orang. Padahal ketersediaan lahan adalah kunci menuju ketahanan pangan.
Ahmad melihat pentingnya peran desa dalam menyediakan lahan-lahan komunal. Supaya warga desa bisa memanfaatkannya untuk mengolah pangan di tengah semakin banyaknya tanah-tanah privat. Dalam konteks ini, dana desa tampaknya bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dana desa itu harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga secara adil dan bijaksana.
Jika itu semua bisa dilakukan, maka ketahanan pangan bukanlah hal yang sulit untuk dicapai. Kuncinya bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi lokal dan membuka ruang seluas-luasnya untuk melibatkan berbagai macam elemen yang ada di desa agar bersama-sama membangun wilayahnya. (*)